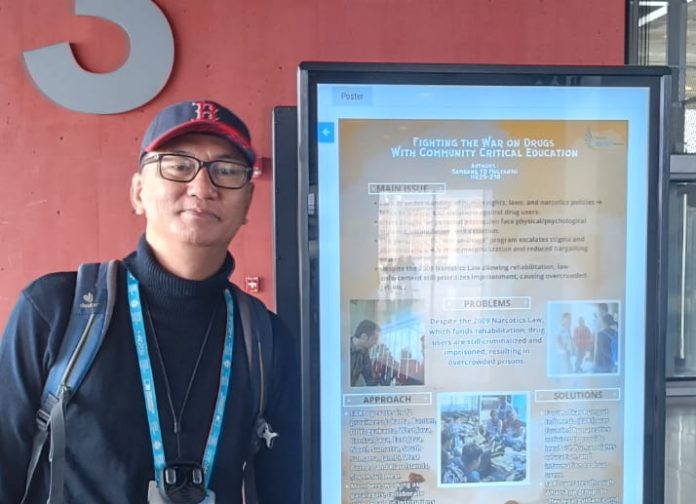Bogordaily.net – Budaya tergesa-gesa atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan kesusu kini menjangkiti hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kita. Dari pengambilan kebijakan publik, hingga program rehabilitasi pengguna narkotika, semuanya seolah ingin serba cepat, instan, dan minim refleksi.
Dalam konteks ini, istilah karbitan layaknya pisang yang dipaksa matang dengan karbit menjadi analogi yang pas untuk menggambarkan arah penanganan narkotika di Indonesia hari ini.
Alih-alih menjadi ruang pemulihan berbasis ilmu dan empati, banyak lembaga rehabilitasi narkotika justru lahir dari semangat pragmatisme.
Rehabilitasi dijalankan bukan atas dasar komitmen terhadap pemulihan, melainkan sebagai peluang ekonomi.
Para klien rehabilitasi pun, yang kebanyakan memiliki mimpi menjadi konselor adiksi atau mendirikan lembaga serupa di kampung halamannya, justru dimasukkan ke skema On the Job Training (OJT) yang bermotif ekonomi.
Mereka didorong menjadi “konselor” instan tanpa pelatihan mumpuni, atau bahkan mendirikan panti sendiri dengan bekal pengalaman terbatas.
Perubahan zaman dan pola penyalahgunaan zat turut memengaruhi kondisi ini. Tren telah bergeser: dari heroin ke amphetamine-type stimulants, synthetic cannabinoids, obat daftar G, hingga analgesik kuat.
Namun, pendekatan rehabilitasi tak kunjung berubah. Akibatnya, banyak lembaga rehabilitasi besar yang dulu dikenal publik mulai kesulitan bertahan.
Klien berkurang drastis, dukungan donor dihentikan, dan lembaga satu per satu gulung tikar.
Situasi diperburuk dengan terbitnya Surat Edaran Bareskrim No. 1/II/2018, yang mewajibkan pengguna narkotika, meskipun tertangkap tanpa barang bukti untuk menjalani rehabilitasi apabila tes urinenya menunjukkan hasil positif.
Secara prinsip, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya pendekatan kesehatan publik terhadap masalah narkotika. Namun dalam praktik, kebijakan ini justru membuka celah penyalahgunaan wewenang.
Alih-alih dibawa ke lembaga resmi yang terdaftar dalam skema Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan mendapat dukungan negara, para pengguna justru dikirim ke rehabilitasi-rehabilitasi karbitan.
Tempat-tempat ini seringkali tak memiliki izin yang sah, dikelola oleh tenaga tanpa pelatihan, dan dijalankan secara asal-asalan.
Yang lebih mengkhawatirkan, muncul praktik kerja sama di bawah tangan antara oknum aparat penegak hukum dengan pengelola lembaga rehabilitasi karbitan.
Dalam praktik ini, pengguna yang tertangkap diarahkan masuk ke lembaga tertentu sebagai bentuk “penyelesaian” perkara.
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan pengguna, tapi juga melanggar prinsip keadilan dan merusak esensi rehabilitasi itu sendiri.
Kita sedang menghadapi industrialisasi rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi tak lagi menjadi ruang aman untuk pemulihan, melainkan berubah menjadi ladang bisnis baru.
Jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki sistem ini, maka bukan hanya para pengguna yang jadi korban, tetapi juga masa depan penanganan narkotika berbasis kesehatan dan hak asasi manusia.
Rehabilitasi bukan sekadar soal tempat atau program. Ia adalah komitmen kolektif untuk memulihkan manusia bukan merampas haknya dengan dalih penyembuhan.
Jika yang kita hadirkan hanya sistem karbitan dengan aktor karbitan pula, maka pemulihan hanyalah mitos. Yang ada hanyalah kegagalan yang berulang dan para pengguna yang semakin terpuruk di tengah sistem yang rusak. (Bambang Yulistyo Tedjo, Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (GRAM))