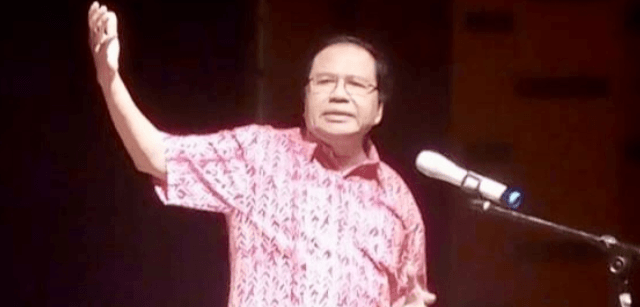Pada awal tahun 1970-an, ketika saya masih seorang mahasiswa di kota Bandung, teman-teman sekelas saya dan saya menyadari bahwa kami perlu mengambil tindakan jika negara kami memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari cengkeraman aturan otoriter.
Karena itu hidup saya dimulai sebagai seorang aktivis politik. Presiden Suharto, yang naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1967, menunjukkan warna yang benar dan jelek setelah apa yang disebut insiden Malari, yang merupakan serangkaian demonstrasi dan kerusuhan mahasiswa pada tahun 1974 setelah kunjungan perdana menteri Jepang.
Itu adalah awal dari akhir kebebasan apa pun yang telah dinikmati oleh orang Indonesia sebelumnya – pers diberangus, serikat buruh menjadi instrumen negara, partai-partai oposisi melemah, dan para kritikus Orde Baru Soeharto dijebloskan ke penjara. Termasuk saya.
Tidak seperti yang lain, saya beruntung. Pada 1979 saya dibebaskan dari penjara setelah satu tahun ditahan. Seorang pengacara HAM terkenal, Adnan Buyung Nasution, datang untuk menyelamatkan saya. Tapi impian saya tentang masa depan yang demokratis harus menunggu hampir dua dekade sebelum itu terpenuhi.
Memasuki 1998. Suharto telah berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun, begitu lama sehingga sulit membayangkan pemerintahannya akan berakhir.
Saya sudah kembali ke Indonesia setelah menempuh studi doktoral saya di Amerika Serikat, dan saya sibuk mengelola think tank ekonomi saya ketika krisis datang.
Baht Thailand runtuh, diikuti segera oleh depresiasi dramatis dari Rupiah Indonesia.
Rasa frustrasi dan amarah yang terpendam terhadap Soeharto, keluarganya dan para kroni korupnya dengan cepat muncul, dan dengan ekonomi yang berantakan, para mahasiswa mengalir ke jalan-jalan di seluruh negeri menuntut pengunduran diri presiden.
Lalu tiba-tiba, suatu hari di bulan Mei, dia akhirnya menyerah dan pergi.
Tidak ada keraguan. Para siswa adalah pahlawan kita. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membawa perubahan.
Indonesia tidak akan pernah bebas dari otoritarianisme tanpa perjuangan mereka.
Seiring berlalunya tahun, kami yakin akan demokrasi kami.
Ketika saya pertama kali memasuki kabinet Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, saya perhatikan banyak rekan saya juga dipenjara selama masa Suharto.
Kami memiliki pengalaman buruk yang serupa, dan sekarang kami berbagi alasan yang sama untuk mengantar Indonesia ke era demokrasi.
Namun, kami lupa sesuatu. Meskipun Suharto adalah sejarah, hantu otoriternya masih ada di antara kita.
Banyak politisi yang pernah menjabat di bawah Soeharto tinggal di dalam pemerintahan.
Kami memiliki jebakan demokrasi – pemilihan terbuka, kebebasan berbicara dan media yang hidup – tetapi yang bersembunyi di balik permukaan adalah orang-orang yang otoriter.
Hanya masalah waktu sebelum mereka kembali.
Saya melihat hantu otoriter kembali jauh kemudian, dimulai pada tahun-tahun awal pemerintahan Joko Widodo yang berkuasa saat saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kelautan.
Presiden, yang bermaksud baik dan ingin menjadikan dirinya sebagai seorang reformis, dihormati oleh sebagian besar orang Indonesia. Tetapi Pak Widodo, yang tidak memiliki partai politik sendiri dan terikat pada keinginan dan kepentingan koalisi yang berkuasa, akhirnya menemukan dirinya terkurung.
Mulai tahun 2017, kami menemukan banyak dari institusi dan norma demokrasi kami secara sistematis dirusak. Saya meninggalkan kabinet, hanya untuk melihat pisau semakin lama.
Legislatif nasional sedang mempersiapkan revisi kejam dari kode kriminal yang membuat kritik presiden menjadi tindak pidana. Legislator juga merencanakan kudeta terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, mengakhiri kemerdekaannya dan mengikat tangannya sehingga hampir mustahil untuk menyelidiki politisi yang korup.
Singkatnya, para politisi ingin memberi tahu konstituen mereka: tutup mulut dan bersikaplah saat kita mencuri, kalau tidak Anda akan masuk penjara.
Perilaku yang keterlaluan, memang, jadi aku tidak terkejut ketika para siswa akhirnya muncul kembali beberapa minggu yang lalu.
Puluhan ribu mahasiswa universitas di seluruh nusantara berduyun-duyun ke jalan-jalan untuk memprotes pengesahan undang-undang baru tentang KPK, menuntut Pak Widodo mengeluarkan keputusan presiden untuk membatalkan kerusakan.
Menyerang meriam air, gas air mata, peluru karet, dan terkadang polisi yang kejam, para siswa juga menuntut presiden untuk menemukan cara untuk membalikkan arah undang-undang hukum pidana.
Sejauh ini, presiden telah meminta legislatif untuk menunda pengesahan hukum pidana sampai DPR baru mengambil kursi mereka akhir bulan ini. Dia juga mengatakan dia akan mempertimbangkan mengeluarkan keputusan presiden untuk melawan hukum KPK.
Jika saya bisa memberi saran kepada Pak Widodo, itu akan memihak siswa. Dia seharusnya mendengarkan mereka, bukan politisi yang mementingkan diri sendiri yang berharap mendapat manfaat dari mengembalikan demokrasi Indonesia.
Rizal Ramli, 30 Oktober 2019.